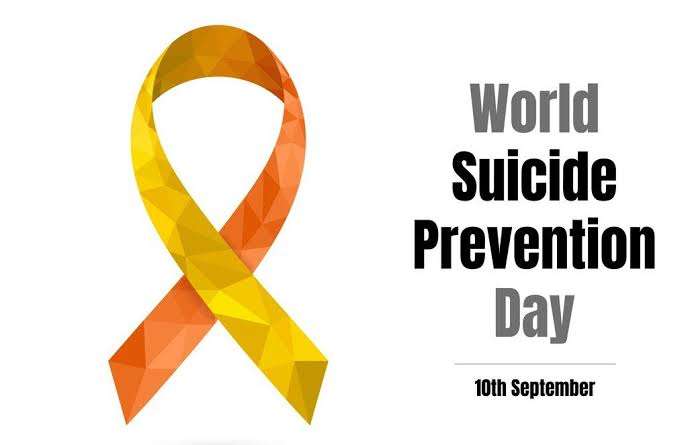Chiki Fawzi dan Kita: Tentang Kesalahan, Martabat, dan Cara Negara Bersikap

Dalam setiap peristiwa publik yang melibatkan figur publik dan otoritas negara, terutama di dunia maya, nyaris mustahil menghilangkan lapisan persoalan yang lebih dalam daripada sekadar menegaskan siapa benar dan siapa yang salah. Pada situasi seperti inilah kita diuji: bagaimana memperlakukan kesalahan tanpa kehilangan sisi kemanusiaan, bagaimana menegakkan etika tanpa merampas martabat anak bangsa, dan bagaimana negara bersikap tegas tanpa tergelincir menjadi ajang penghukuman simbolik semata.
Keputusan mencopot keterlibatan Marsha Chikita Fawzi (Chiki Fawzi) sebagai salah satu petugas haji, membuka ruang refleksi kita. Peristiwa ini bukan hanya tentang seorang individu, melainkan tentang kita semua sebagai masyarakat yang sangat berpotensi mengalami hal yang sama. Apalagi kita sedang hidup dan bergerak dalam logika moral publik di era yang sangat terdominasi oleh keputusan algoritma.
Chiki Fawzi menjadi satu dari kurang lebih enam orang yang dicopot atau dipulangkan, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri yang mengurus soal Haji dan Umrah kepada media. Alasan pencopotannya beragam, mulai dari faktor kesehatan hingga pelanggaran ketentuan pelatihan (faktabanten.co.id).
Namun peristiwa administratif semacam ini hampir tak pernah berdiri sebagai fakta tunggal, sebab selalu hadir bersamaan dengan cara masyarakat memberi makna, menilai, dan menghakimi.
Dari sudut pandang ini, kasus Chiki Fawzi menjadi gambaran bagaimana masyarakat modern memperlakukan kesalahan publik figur, dan apakah setiap kesalahan harus berujung menyudutkan martabatnya. Pada titik ini, persoalan tidak lagi berhenti pada tindakan administratif, melainkan bergeser pada prinsip yang lebih mendasar: hak individu untuk tetap dihormati bahkan ketika ia keliru atau dinilai melanggar norma.
Apakah pencopotan tersebut sudah proporsional? Bagaimana negara menjaga human dignity? Dan di mana batas antara disiplin institusional dan penghukuman simbolik?
Pertanyaan-pertanyaan ini mengarah pada isu sentral: bagaimana negara menempatkan diri dan bersikap atas persoalan yang tak mesti menjadi rumit jika seandainya terjadi semacam ‘berbalas pantun’ antara Wamen dan yang dicopot jadi petugas.
Fokusnya semestinya pada tindakan negara, bukan pada gosip personal tentang Chiki Fawzi yang justru berisiko menyerang sisi privat dan personalnya. Terlebih, negara dalam hal ini berperan sebagai pengelola simbol kesucian ritual rukun Islam kelima, yakni ibadah haji—sebuah ruang yang sarat nilai moral dan religius.
Dalam konteks inilah, bahasa dan pernyataan pejabat publik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan itu sendiri. Pernyataan pejabat kementerian urusan haji bahwa “petugas haji jangan nebeng haji” tidak hanya berfungsi sebagai penegasan etik, tetapi juga bekerja dalam ruang simbolik yang bisa dimaknai luas dan liar. Ia berpotensi memperkuat stigma dan memperpanjang hukuman sosial di luar keputusan administratif.
Bahasa negara bukan sekadar mengatur perilaku, tetapi juga membentuk cara publik memandang individu yang tengah berada di pusaran kebijakan dan sorotan warganet.
Ketegasan etik tidak cukup berhenti pada pernyataan; ia menuntut konsistensi struktural. Idealnya, negara dan masyarakat saling menguatkan dalam membentuk siklus moralisasi yang sehat, dengan kesiapan institusional untuk memastikan bahwa standar yang ditegakkan benar-benar berlaku merata tanpa keistimewaan kelompok atau individu tertentu.
Tanpa konsistensi tersebut, ketegasan mencopot Chiki Fawzi sebagai petugas haji 2026 justru berisiko melahirkan persoalan etik baru. Sebab perlu dicatat, ketegasan yang diarahkan pada putri Ikang Fawzi dan mendiang Marissa Haque ini akan kehilangan bobot etiknya apabila kelak ditemukan praktik serupa “nebeng naik haji” pada petugas lain yang lolos dan resmi mendampingi jemaah di Arab Saudi 2026 ini. Jika itu luput dari perhatian negara, ia akan menjadi preseden buruk dan tertawaan para netizen Indonesia.
Situasi semacam ini memperlihatkan kepada kita, bahwa keadilan moral tidak bisa hanya berhenti pada keputusan negara. Tanpa partisipasi dan pengawasan publik, sikap tegas mudah berubah menjadi simbolik semata. Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi penting untuk memastikan standar etika diterapkan secara konsisten bin istiqomah, bukan sekadar berbasis pada kasus yang ramai di media sosial semata.
Namun relasi tersebut sering kali tidak netral, terutama ketika menyangkut tubuh dan moral. Standar moral yang lebih ketat pada perempuan, tubuh perempuan sebagai medan kontrol simbolik, serta ekspektasi kesalehan visual dalam ruang keagamaan menjadi sorotan tersendiri dalam kasus-kasus seperti ini.
Seluruh dinamika tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi institusional kementerian Haji dan Umrah saat ini. Kementerian baru ini mewarisi krisis kepercayaan publik akibat kasus korupsi masa lalu yang menggerogoti legitimasi pengelolaan ibadah haji, sekaligus menghadapi tekanan dari jutaaan pasang mata agar mereka tampil bersih, tegas, dan betul-betul serius untuk berubah dan kembali ke trek lurus. Kebijakan mereka pun semestinya tidak lagi sekadar soal teknis, melainkan juga pada manajemen persepsi moral.
“Kezaliman kerap lahir bukan dari niat buruk, melainkan dari keyakinan yang terlalu yakin pada dirinya sendiri saat mereka melahirkan keputusan atas nama negara.”
ANSHAR AMINULLAH
Di Antara Reformasi dan Keadilan Individual
Ketika reformasi institusi berpotensi mengorbankan individu, pertanyaan mendasarnya adalah apakah keadilan prosedural tetap dijaga? Selalu ada risiko overcorrection pasca-skandal besar, ketika semangat membersihkan institusi justru menciptakan ketegangan antara kepentingan institusional dan martabat personal.
Karena itu, reformasi sejati membutuhkan sistem, bukan hanya sanksi. Ia menuntut evaluasi rekrutmen, pembinaan, dan pengawasan, serta kemampuan membedakan secara jernih antara kesalahan personal dan kejahatan struktural.
Untuk memahami kompleksitas pertemuan antara individu dan institusi tersebut, refleksi pemikiran moral menjadi relevan sekaligus menjadi renungan seperti yang Hannah Arendt pernah ingatkan:
“The sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be either good or evil.”
Bahwa kebenaran yang menyedihkan adalah, sebagian besar keburukan dilakukan oleh orang-orang yang tidak pernah benar-benar berniat menjadi baik atau jahat.
Refleksi ini menegaskan bahwa persoalan etika tidak selalu berangkat dari niat jahat, melainkan sering lahir dari keyakinan yang merasa paling benar.
Kita tentu berharap ada hikmah terbaik yang dititipkan Allah dalam peristiwa ini, baik bagi Chiki Fawzi maupun semua pihak terkait terlebih pada warga nitizen kita.
Harapan tersebut tidak boleh mengaburkan kewaspadaan etis kita, bahwa dalam tradisi moral apa pun, kekuasaan yang kehilangan kerendahan hati sangat berisiko berubah dari penegakan etika menjadi ketidakadilan yang luput disadari.
Karena itu, kementerian Haji dan Umrah patut mengingat satu hal penting dalam keyakinan moral dan keagamaan yang menjadi pijakan bersama, bahwa kezaliman kerap lahir bukan dari niat buruk, melainkan dari keyakinan yang terlalu yakin pada dirinya sendiri saat mereka melahirkan keputusan atas nama negara. Wallahu A’lam.
Artikel ini lebih awal telah diterbitkan oleh media di bawah kemudian diposting ulang oleh penulis sebagai arsip pribadi dan kumpulan tulisan pribadi